Merah Putih One For All, Ambisi Nasionalisme yang Tersandung di Dunia Animasi
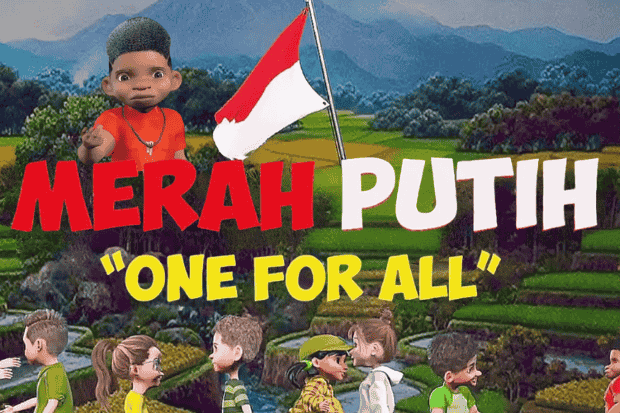
Di tengah gegap gempita persiapan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, sebuah karya animasi lokal diluncurkan dengan misi besar: menyalakan semangat persatuan dan kebanggaan nasional di hati anak-anak dan generasi muda. Judulnya Merah Putih, One For All, atau kerap disingkat One For All. Namun, bukannya menuai pujian, film ini justru menjadi topik panas di media sosial karena kritik tajam terhadap kualitasnya.
Fenomena ini menarik, bukan hanya karena kasusnya viral, tetapi juga karena ia membuka diskusi lebih luas tentang industri animasi Indonesia, penggunaan dana publik, dan ekspektasi penonton modern.
Mimpi Besar di Balik Film
Film ini awalnya dipromosikan sebagai karya yang sarat pesan kebangsaan. Menggabungkan tokoh-tokoh hewan sebagai simbol karakter bangsa, One For All dirancang untuk menjadi tontonan keluarga yang penuh nilai positif: persatuan, kerja sama, dan semangat gotong royong.
Rencana perilisan bertepatan dengan momen HUT RI jelas bukan kebetulan. Dalam kacamata pemasaran, ini adalah waktu emas penonton sudah terhanyut dalam atmosfer nasionalisme, dan bioskop menjadi tempat yang tepat untuk menyampaikan pesan moral.
Di atas kertas, premis ini solid. Jarang sekali industri animasi Indonesia merilis film layar lebar yang secara terang-terangan menonjolkan tema nasionalisme. Harapan publik sempat menguat apalagi disebut-sebut bahwa produksi ini menelan biaya sekitar Rp 6,7 miliar.
Antusiasme yang Cepat Berubah
Sayangnya, semua berubah begitu trailer resmi dirilis. Alih-alih memicu gelombang antusiasme, video promosi tersebut langsung dibanjiri komentar miring. Kritik utamanya: kualitas visual yang dinilai jauh dari standar film layar lebar masa kini.
Pergerakan karakter terlihat kaku, pencahayaan seadanya, dan ekspresi wajah kurang hidup. Tak sedikit warganet yang membandingkannya dengan grafis game era PlayStation 2 atau animasi sinetron anak-anak dari awal dekade 2000-an. Bukan hanya itu, detail suara juga disorot. Dialog terdengar seperti hasil dubbing kilat, tanpa intonasi alami. Satu adegan bahkan menjadi bahan lelucon karena suara burung yang terdengar seperti… monyet.
Isu Aset Beli dan Orisinalitas
Kontroversi makin memanas ketika beredar informasi bahwa banyak aset 3D yang digunakan bukan hasil kreasi tim animator dari nol, melainkan dibeli dari platform Reallusion dan hanya dimodifikasi. Praktik ini memang umum di industri untuk menghemat waktu, tetapi publik menilai, untuk proyek sebesar ini dan dengan biaya miliaran rupiah, langkah tersebut tidak pantas jika tidak diimbangi kreativitas dan modifikasi signifikan.
Bagi penonton awam, ini menimbulkan kesan bahwa film tersebut “dibuat terburu-buru” dan kurang melibatkan talenta lokal secara penuh.
Dana Fantastis, Hasil Minim

Isu anggaran menjadi bahan bakar terbesar dalam kritik publik. Nilai Rp 6,7 miliar jelas bukan jumlah sepele, terlebih bagi industri film animasi Indonesia yang lingkup produksinya masih terbatas. Warganet mulai mempertanyakan: ke mana saja uang tersebut dialokasikan? Apakah lebih banyak habis di produksi atau di biaya non-kreatif seperti promosi dan acara seremonial?
Kecurigaan ini diperkuat oleh perbedaan mencolok antara ekspektasi dan hasil akhir. Banyak yang merasa, dengan dana sebesar itu, seharusnya kualitas animasi bisa jauh lebih baik, bahkan jika menggunakan aset beli sekalipun.
Media Sosial, Arena Kritik dan Sindiran
Ketika sebuah karya masuk ke ranah publik, ia tak lagi sepenuhnya milik pembuatnya netizen punya kuasa untuk menilainya. Dalam kasus One For All, media sosial menjadi arena terbuka untuk kritik pedas bercampur humor sarkastik.
Meme bermunculan, membandingkan cuplikan film dengan gambar lucu atau potongan animasi lawas. Bahkan akun resmi bioskop seperti CGV ikut terseret, ketika admin mereka merespons komentar penonton dengan nada menahan tawa.
Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya persepsi publik terbentuk dan betapa sulitnya mengubahnya ketika opini negatif sudah viral.
Sindiran dari Sesama Kreator
Bukan hanya penonton biasa yang mengkritik, tetapi juga kreator animasi profesional. Sutradara Jumbo (film animasi sukses Indonesia) secara halus menyentil lewat media sosial, menekankan pentingnya niat tulus dan kualitas pengerjaan, bukan sekadar menyelesaikan proyek.
Sindiran ini memperkuat anggapan bahwa masalah One For All bukan sekadar “selera”, melainkan soal standar industri yang tidak terpenuhi.
Pelajaran untuk Industri Animasi Indonesia
Kasus One For All bisa menjadi momentum refleksi bagi industri animasi Indonesia. Beberapa pelajaran penting yang bisa dipetik:
- Transparansi Anggaran: Proyek yang didanai publik atau melibatkan sponsor besar perlu keterbukaan soal penggunaan dana. Ini menghindari kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan.
- Investasi pada Talenta Lokal: Alih-alih mengandalkan aset beli, industri perlu memperkuat ekosistem animator lokal, memberi mereka waktu dan sumber daya memadai untuk berkarya.
- Ekspektasi Publik yang Meningkat: Penonton Indonesia kini terbiasa menonton animasi kelas dunia di platform streaming. Standar mereka sudah tinggi, sehingga karya lokal harus berusaha setara, setidaknya dalam hal cerita dan kekuatan visual.
- Pentingnya Uji Kelayakan Sebelum Rilis: Trailer adalah pintu pertama untuk menarik minat. Jika justru memicu kritik, mungkin rilis perlu ditunda untuk revisi.
Antara Niat Baik dan Eksekusi
Perlu diakui, niat di balik One For All tidak bisa diremehkan. Menghadirkan film yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan adalah tujuan mulia. Namun, dalam industri kreatif, niat baik saja tidak cukup. Eksekusi menentukan apakah pesan akan sampai atau justru hilang di tengah tawa dan sindiran.
Bagaimana Seharusnya Tanggapan Produser?

Di tengah badai kritik, produser memiliki dua pilihan: defensif atau responsif. Sikap defensif mungkin melindungi harga diri sesaat, tetapi jarang meredam kontroversi. Sebaliknya, sikap responsif misalnya, mengakui kekurangan, menjelaskan proses produksi, atau bahkan berjanji melakukan perbaikan bisa membuka peluang memulihkan kepercayaan publik.
Sayangnya, dalam kasus ini, komunikasi dari pihak pembuat terbilang minim. Kesempatan untuk menjelaskan atau mengajak publik berdialog belum dimanfaatkan maksimal.
Harapan di Tengah Kritik
Meski One For All mendapat hujan kritik, bukan berarti harapan untuk animasi Indonesia pupus. Justru, ini bisa menjadi titik balik jika industri mau belajar dan berbenah. Kita sudah melihat contoh sukses seperti Si Juki The Movie atau Nussa yang membuktikan bahwa animasi lokal bisa bersaing jika digarap serius.
Penutup
Perjalanan Merah Putih: One For All menjadi teguran keras bahwa mimpi besar hanya akan berarti jika diwujudkan dengan eksekusi yang benar-benar matang. Di era digital, publik bukan hanya penonton, tetapi juga kritikus aktif yang suaranya bisa mengangkat atau menjatuhkan sebuah karya dalam hitungan jam.
Semoga kedepan, setiap proyek animasi Indonesia tidak hanya mengandalkan semangat nasionalisme sebagai jualan, tetapi juga menghadirkan kualitas yang membuat publik merasa bangga bukan sekadar terhibur, tapi juga terinspirasi. Karena pada akhirnya, film adalah seni yang hidup dari kepercayaan dan cinta penontonnya.







